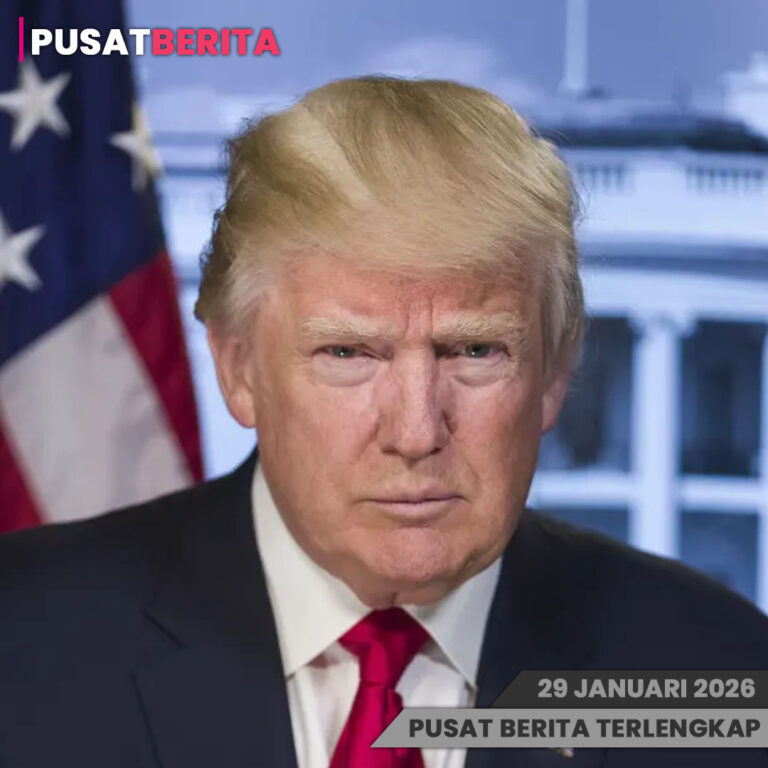Jakarta – Serangan Amerika Serikat (AS) ke tiga fasilitas nuklir Iran pada Minggu (22/6/2025), menandai eskalasi tajam dalam konflik segitiga antara Iran, Israel, dan AS yang selama ini terpendam di balik diplomasi tumpul dan operasi militer berskala terbatas.
Peristiwa ini mencerminkan bergesernya norma dalam menyelesaikan konflik antarnegara: dari meja perundingan kembali ke logika kekuatan senjata. Pada saat yang sama, risiko penutupan Selat Hormuz membayangi ekonomi global yang tengah rapuh, dengan harga energi yang bisa melonjak drastis dan mengancam stabilitas fiskal negara-negara berkembang.
Melihat kompleksitas situasi ini, para pengamat mencoba membaca arah perkembangan konflik, baik dari sisi dinamika kekuatan politik regional maupun implikasi serius terhadap stabilitas ekonomi dunia. Berikut pandangan mereka:
“Saya rasa negara-negara lain baik di kawasan Timur Tengah ataupun major powers yang berada di luar kawasan cenderung mendorong de-eskalasi sesegera mungkin. Tidak ada negara yang ingin peperangan ini berlarut-larut, selain mungkin Israel dan Iran sendiri. Seperti yang kita ketahui, axis of resistance yang selama ini menjadi sekutu Iran di kawasan semakin lemah karena rentetan serangan yang dilakukan oleh Israel. Sebut saja Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza yang masih terlibat peperangan dengan Israel. Mungkin tinggal Houthi di Yaman yang masih memiliki cukup kekuatan. Namun, mereka cenderung tidak mampu mengungguli kekuatan militer Israel dan AS,” demikian disampaikan Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Irfan Ardhani, Senin (23/6).
“Di sisi lain, banyak negara-negara Arab yang memiliki kedekatan strategis dengan AS dan cenderung tidak sejalan dengan Iran. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin serangan yang dilakukan oleh AS tersebut sesuai dengan kepentingan mereka. Yang menjadi pertanyaan, apa langkah retaliasi yang disiapkan oleh Iran terhadap AS? Apakah mereka akan benar-benar menutup Selat Hormuz? Jika hal ini terjadi maka akan makin banyak negara yang terdampak secara langsung oleh eskalasi tersebut karena harga minyak dunia akan meningkat secara drastis maka makin banyak yang berkepentingan menyelesaikan konflik baik secara damai maupun tidak.”
Jika Iran menutup Selat Hormuz, ungkap Irfan, selalu ada kemungkinan bagi Presiden Donald Trump untuk memerintahkan serangan kembali.
“Ini adalah bentuk penyelesaian sengketa dalam ‘position of strength’ yang selalu diidam-idamkan olehnya. Sementara itu, bernegosiasi justru membuat Iran merasa di atas angin. Jika Iran tidak menutup Selat Hormuz, mereka mungkin sedang berusaha mencari solusi di atas meja perundingan sembari menjaga martabat agar tidak semakin kehilangan muka,” terang Irfan.
Arti dari serangan AS, sebut Irfan, adalah episode berulang terhadap pelanggaran hukum internasional.
“Hukum internasional yang selama ini diharapkan membatasi tindakan negara terbukti tidak efektif,” kata Irfan, yang meyakini bahwa Rusia dan China cenderung mendorong de-eskalasi sembari mengutuk serangan AS.
Menduga Target Serangan Balasan Iran

Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Smith Alhadar menduga serangan balasan Iran akan menargetkan pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah.
“Sepanjang negara Arab tidak mengizinkan wilayahnya digunakan AS (untuk menyerang Iran), perang regional bisa dikendalikan,” sebut Smith saat ditanya mengenai potensi meluasnya konflik pasca Amerika serang Iran.
Ada dua fenomena yang diyakini Smith membuat eskalasi Iran versus AS dan Israel tidak berkepanjangan.
“Di luar dugaan Israel dan AS, ternyata rudal-rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan berlapis Israel. Hal ini merepotkan Israel. Sementara Trump dikecam sebagian anggota Kongres karena menyerang negara lain tanpa persetujuan kongres. Melihat dua fenomena ini, terbuka kemungkinan perang tidak berkepanjangan karena terlalu mahal bagi Israel dan AS. Iran juga pasti tidak menghendaki perang berlarut-larut yang menguras sumber dayanya. Tapi harus dicari exit strategy yang bisa menghentikan perang dengan menyelamatkan muka semua pihak yang terlibat,” ujar Smith, yang mengakui bahwa program nuklir Iran menjadi tantangan utama di meja perundingan.
Ditanyakan bagaimana posisi Arab Saudi, Turki, Rusia, dan China dalam eskalasi ini, Smith menilai, “Mereka akan menahan diri, bahkan akan melakukan de-eskalasi. Tapi kalau perang berkepanjangan, langsung atau tidak langsung, semua negara di atas akan terseret ke dalamnya untuk menyelamatkan kepentingan nasional masing-masing. Rusia dan China, khususnya, tak mau ada perubahan rezim di Iran, terutama munculnya rezim baru yang pro-Barat.”
Senada dengan Smith, Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah meyakini bahwa serangan balasan Iran atas AS akan menargetkan pangkalan militer AS di beberapa negara di Timur Tengah.
“Terutama sekali negara yang kemarin menyukseskan penyerangan AS atas instalasi nuklir Iran,” kata Rezasyah.
Rezasyah menuturkan bahwa konflik berpotensi meluas karena Trump tidak memerintahkan Israel mengakhiri kekerasan yang dimulainya terhadap Iran.
“Keadaan ini cenderung memaksakan Iran mempertahankan diri dengan terus menyerang Israel… Saat ini AS dan Israel sangat tersudut. Karena mereka terbukti menjadi penyebab dari krisis Internasional yang berpotensi menjadi Perang Dunia III,” ungkap Rezasyah.
Adapun negara kekuatan besar lainnya diperkirakan Rezasyah masih menahan diri untuk tidak terlibat.
“Mereka akan turun guna mencegah, jika perang berpotensi menggunakan senjata nuklir,” beber Rezasyah.
Dampak Ekonomi Perang: Energi, Inflasi, dan Ancaman Krisis Global
Dari sisi ekonomi, salah satu skenario terburuk yang paling dikhawatirkan adalah penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menegaskan bahwa jika skenario ini terjadi, dampaknya akan langsung mengguncang pasar energi global dan menjalar ke berbagai sektor strategis di banyak negara.
“Penutupan Selat Hormuz akan menjadi guncangan besar bagi pasar energi global. Sekitar 20–25 persen pasokan minyak dunia melewati selat sempit ini setiap hari. Jika Iran benar-benar menutup jalur tersebut, harga minyak mentah global dapat melonjak ke level USD 120–130 per barel, sebagaimana diperkirakan oleh Oxford Economics. Lonjakan ini akan memicu inflasi global dan menghantam daya beli masyarakat lintas negara. Sektor paling rentan terdampak adalah transportasi, manufaktur energi-intensif, dan sektor logistik global yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil,” jelas Karimi.
“Negara-negara berkembang akan paling merasakan dampaknya, karena mereka memiliki ruang fiskal dan moneter yang lebih sempit untuk menyerap tekanan harga energi.”
Karimi menambahkan, “Negara-negara seperti China, India, dan Uni Eropa belum cukup siap menghadapi disrupsi total dari Selat Hormuz. Meskipun mereka telah berupaya melakukan diversifikasi energi—melalui energi terbarukan, peningkatan kapasitas cadangan strategis, dan pembelian dari negara non-OPEC—realitasnya, sebagian besar kebutuhan minyak mereka masih bersumber dari kawasan Teluk. Infrastruktur pipa dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mem-bypass Hormuz memiliki kapasitas terbatas dan belum bisa menggantikan jalur laut sepenuhnya maka jika pasokan terganggu, negara-negara ini akan menghadapi kenaikan harga energi domestik, lonjakan biaya produksi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Mereka harus segera memperkuat cadangan energi nasional dan mempercepat transisi energi sebagai langkah mitigasi jangka menengah.”
Indonesia, kata Karimi, akan menghadapi tekanan berat jika Selat Hormuz terganggu.
“Harga minyak dunia yang melonjak akan berdampak langsung pada harga impor minyak mentah dan produk BBM, sehingga meningkatkan beban subsidi energi. Pemerintah terpaksa mengalokasikan anggaran tambahan untuk menjaga stabilitas harga BBM atau membiarkan harga pasar melonjak yang akan menggerus daya beli masyarakat. Depresiasi rupiah akibat arus keluar modal juga memperburuk situasi, memicu imported inflation dan mempersempit ruang kebijakan moneter,” ungkap Karimi.
“Bank Indonesia harus segera memperkuat intervensi di pasar valuta asing dan menstabilkan ekspektasi pelaku pasar. Kementerian Keuangan (RI) juga perlu mengkaji ulang APBN dan menyesuaikan kebijakan fiskal untuk menampung lonjakan belanja subsidi. Di saat yang sama, pemerintah wajib memastikan komunikasi publik berjalan efektif untuk meredam kepanikan pasar. Krisis ini bukan hanya soal harga energi, namun menyangkut ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.”