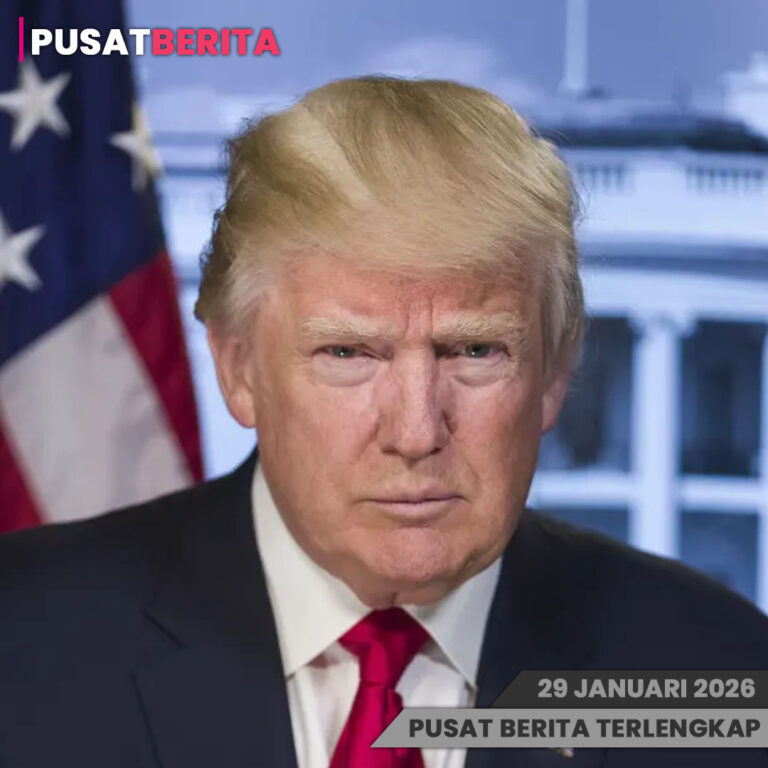Gaza – Kengerian perang belum beranjak dari Jalur Gaza. Kematian, luka, dan mereka yang terbaring sekarat telah menjadi pemandangan sehari-hari dari wilayah kantong Palestina itu selama lebih dari 19 bulan terakhir.
Bukan ledakan atau teriakan yang paling keras terdengar, melainkan keluhan sunyi dari perut-perut kosong yang menjerit dalam diam.
Kelaparan di Gaza bukan sekadar tidak ada makanan; namun telah menjelma menjadi senjata mematikan, yang membunuh pelan, tanpa suara.
Dan di tengah situasi yang nyaris mustahil bagi kehidupan baru untuk tumbuh dan bertahan lahirlah Siwar Ashour dengan berat hanya 2,5 kilogram.
Sejak lahir pada 20 November 2024, Siwar mengalami kelainan kerongkongan yang menyulitkannya minum ASI, membuatnya bergantung pada susu formula khusus—yang kini nyaris tidak tersedia di Gaza.
Rumah orang tua Siwar di al-Nuseirat sudah hancur akibat pengeboman di awal perang, yang dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel, dan kemudian memicu serangan balik yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 53.000 orang di Gaza.
Mereka sempat tinggal di tenda, namun sangat sulit mendapatkan makanan dan air. Pada saat yang sama, kamp mereka menjadi sasaran tembakan Israel.
Keluarga Siwar pun kembali ke al-Nuseirat untuk tinggal di rumah kakek dan neneknya, namun rumah itu dibom. Satu-satunya yang tersisa hanyalah sebuah kamar kecil yang mereka tempati bersama 11 orang lainnya. Di sinilah Siwar dilahirkan.
“Saya selalu kelelahan. Tidak ada privasi dan saya tidak bisa beristirahat sama sekali,” kata Najwa Aram, ibu Siwar yang berusia 23 tahun seperti dilansir The Guardian. “Tidak ada makanan atau nutrisi yang layak dan ketika saya melahirkan dia, dia berbeda dengan bayi lainnya.”
“Saat lahir, dia terlihat cantik meskipun wajahnya menunjukkan kelemahan. Sekarang tubuhnya sangat kurus, tampak tak wajar. Bayi seusianya seharusnya memiliki berat sekitar 6 kilogram atau lebih — bukan hanya 2 hingga 4 kilogram.”
Bulan lalu Najwa mengetahui bahwa dia hamil anak kedua dan dia hidup dalam ketakutan akan kehilangan Siwar sebelum adiknya lahir. Najwa kini sudah pindah ke Khan Younis dan tinggal bersama ibunya, namun sebagian besar waktunya dihabiskan di Rumah Sakit Nasser bersama putrinya.
Suami Najwa, Saleh, buta dan terpaksa tetap tinggal di al-Nuseirat.
“Meski ayah Siwar buta, dulu dia sering bermain dengannya,” tutur Najwa. “Dia hanya sempat mengunjungi kami sekali di rumah sakit karena dia tidak bisa pergi ke mana-mana tanpa ada yang menemaninya. Dia lebih takut kehilangan Siwar dibandingkan saya — dia sangat terikat dengannya.”
Keluarga ini tidak memiliki sumber penghasilan, sehingga mereka bergantung pada dapur amal untuk mendapatkan makanan dan bantuan kemanusiaan.
“Saya sendiri menderita kekurangan gizi. Namun, tetap berusaha menyusui Siwar, meski dia menolak dan terus menangis,” ungkap Najwa.
Untuk itu, blokade terbaru Israel sejak 2 Maret 2025 yang melarang semua barang, termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan masuk ke Gaza tidak hanya membahayakan nyawa Siwar, namun juga orang tuanya, dan jelas warga Palestina lainnya.
Jerit Dokter di Gaza: Lihatlah Kami Sebagai Manusia

Dr. Ahmed al-Farah, direktur gedung anak dan ibu di Rumah Sakit Nasser, menjelaskan bahwa setiap hari pihaknya mencatat antara lima hingga 10 kasus baru kekurangan gizi.
“Kami melihat kasus-kasus yang sangat parah. Kekurangan gizi pada anak-anak tampak dengan cara yang mengerikan dan sangat mencolok,” kata Ahmed. “Kami tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka. Mereka butuh protein, namun tidak ada. Kami hanya bisa memberikan sedikit susu, kadang susu bubuk, namun tak bisa lebih dari itu.”
Dia menambahkan bahwa kepadatan pasien yang sangat tinggi memperparah situasi.
“Kepadatan luar biasa di rumah sakit menyebabkan penyebaran penyakit di kalangan anak-anak semakin cepat,” tutur Ahmed.
Kondisi logistik di rumah sakit, sebut Ahmed, mengkhawatirkan.
“Kami benar-benar tak berdaya memenuhi kebutuhan mereka—kami tidak bisa menyediakan makanan, suplemen, obat-obatan, atau vitamin yang sesuai dengan kondisi anak-anak ini,” kata Ahmed. “Saya dulu hanya membaca tentang kekurangan gizi di buku teks kedokteran. Saya pikir itu hanya teori, sesuatu yang tidak akan kami saksikan secara langsung. Namun kini, semua yang tertulis di buku itu hadir nyata di depan mata kami, di Gaza.”
“Saya memohon kepada dunia: tolong lihatlah kami sebagai manusia—kami diciptakan sama seperti yang lainnya.”
57 Anak di Gaza Meninggal Akibat Kekurangan Gizi

Sejak dimulainya blokade bantuan pada 2 Maret, otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa 57 anak meninggal akibat dampak dari kekurangan gizi. Apabila situasi ini terus berlanjut, diperkirakan hampir 71.000 anak di bawah usia lima tahun akan mengalami kekurangan gizi akut dalam 11 bulan ke depan.
Dalam pengarahan kepada para jurnalis di Jenewa, perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Wilayah Pendudukan Palestina Rik Peeperkorn mengungkapkan bahwa embargo total bantuan oleh Israel telah menyebabkan WHO hanya memiliki persediaan yang cukup untuk merawat sekitar 500 anak dengan kondisi kekurangan gizi akut. Jumlah ini, menurutnya, hanya sebagian kecil dari kebutuhan yang sangat mendesak.
Dia memperingatkan bahwa warga Gaza kini terperangkap dalam siklus mematikan, di mana kurangnya keragaman makanan, kekurangan gizi, dan penyakit saling memperparah satu sama lain.
Pernyataan Peeperkorn muncul bersamaan dengan dirilisnya analisis terbaru Integrated Food Security Phase Classification (IPC)—skala peringatan ketahanan pangan— pada Senin (12/5). Dalam laporan tersebut terungkap bahwa satu dari lima warga Gaza atau sekitar 500.000 orang, berada di ambang kelaparan. Sementara itu, seluruh populasi Gaza yang berjumlah 2,1 juta orang kini menghadapi kekurangan pangan berkepanjangan.
“Ini adalah salah satu krisis kelaparan terburuk di dunia yang sedang berlangsung secara nyata di depan mata kita,” tegas Peeperkorn.
Dalam kesempatan yang sama, Peeperkorn menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara, tempat di mana lebih dari 300 anak diperiksa setiap hari di pusat nutrisi yang didukung WHO. Selama kunjungan itu, rumah sakit melaporkan bahwa lebih dari 11 persen anak-anak yang diperiksa mengalami kekurangan gizi akut secara global.
“Saya melihat mereka langsung di bangsal… Seorang anak berusia lima tahun, namun saya kira usianya baru dua setengah tahun,” ujarnya.
Saat ini, WHO mendukung 16 pusat pengobatan rawat jalan dan tiga pusat rawat inap untuk perawatan kekurangan gizi di Gaza. Bantuan ini mencakup pasokan penting yang menyelamatkan nyawa. Namun, penghentian pengiriman bantuan oleh Israel sangat mengancam keberlangsungan operasi-operasi ini.
Peeperkorn menekankan bahwa kekurangan gizi dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang bisa berlangsung seumur hidup, seperti pertumbuhan yang terhambat, perkembangan kognitif yang terganggu, dan berbagai masalah kesehatan lainnya.
“Tanpa makanan bergizi yang cukup, air bersih, dan akses terhadap layanan kesehatan, satu generasi penuh akan terdampak secara permanen,” jelasnya.
Peeperkorn menyatakan bahwa WHO telah secara terus-menerus menyampaikan kepada otoritas Israel soal pentingnya mengizinkan pasokan bantuan masuk ke Gaza.
“Kita tidak perlu menunggu adanya deklarasi kelaparan di Gaza untuk menyadari bahwa orang-orang sudah mengalami kelaparan, sakit, dan bahkan meninggal, sementara makanan dan obat-obatan hanya berjarak beberapa menit dari perbatasan,” tutur Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Laporan hari ini menunjukkan bahwa tanpa akses segera terhadap makanan dan kebutuhan pokok, situasi akan terus memburuk, menyebabkan lebih banyak kematian dan terjerumus ke dalam kelaparan.”
Mengutip situs UNHCR, kelaparan hanya dapat dideklarasikan ketika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. PBB menggunakan skala IPC yang terdiri dari lima fase untuk menilai situasi ketahanan pangan suatu wilayah.
Klasifikasi kelaparan merupakan tingkat tertinggi dalam skala IPC atau Fase 5. Kriterianya meliputi:
- Setidaknya 20 persen dari populasi mengalami kekurangan pangan ekstrem
- Tingkat malnutrisi akut melebihi 30 persen
- Dua orang per 1.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan
Kehabisan Kata-kata atas Penderitaan Gaza

Komisaris Jenderal UNRWA, badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini mengaku dia mulai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan penderitaan dan tragedi yang menimpa warga Gaza.
“Mereka sudah lebih dari dua bulan tanpa bantuan,” ujarnya seperti dikutip BBC.
“Kelaparan makin meluas, orang-orang kelelahan, orang-orang kelaparan… kita bisa perkirakan dalam beberapa minggu ke depan jika tidak ada bantuan yang masuk, orang-orang tidak akan mati karena bom, namun karena kekurangan makanan. Ini adalah penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai senjata perang.”
Ketika ditanya apakah dia sependapat dengan mereka yang menuduh Israel menggunakan blokade bantuan kemanusiaan sebagai senjata perang terhadap warga sipil, Lazzarini menjawab, “Saya tidak ragu sedikit pun bahwa itulah yang kita saksikan selama 19 bulan terakhir ini, terutama dua bulan terakhir. Ini adalah kejahatan perang. Penilaian kuantitatif akan datang dari Mahkamah Internasional (ICJ), bukan dari saya. Namun, yang bisa saya sampaikan, yang kami lihat dan amati, adalah bahwa makanan dan bantuan kemanusiaan memang digunakan untuk mencapai tujuan politik atau militer dalam konteks Gaza.”
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, tidak menyembunyikan strategi pemerintahnya. Bulan lalu, Katz menyatakan bahwa blokade terhadap Gaza merupakan cara utama yang digunakan untuk menekan Hamas demi meraih kemenangan dan membebaskan seluruh sandera yang masih ditahan.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendukung pernyataan Katz.
“Penghentian bantuan kemanusiaan adalah salah satu cara utama untuk memberikan tekanan terhadap Hamas. Mengembalikan bantuan ke Gaza sebelum Hamas bertekuk lutut dan membebaskan semua sandera kita akan menjadi sebuah kesalahan bersejarah,” sebut Ben-Gvir.
PBB dan kelompok-kelompok bantuan utama tegas menolak klaim Israel bahwa Hamas mencuri dan mengendalikan distribusi makanan yang masuk ke Gaza. Mereka menolak bekerjasama atas skema yang diusulkan Israel dan Amerika Serikat (AS), yang akan menggunakan perusahaan keamanan swasta untuk mendistribusikan bantuan.
“Rencana distribusi khusus ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar kami, termasuk prinsip ketidakberpihakan, netralitas, dan independensi. Karena itu, kami tidak akan berpartisipasi di dalamnya,” kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq pada Kamis (15/5).
Melansir Al Jazeera, Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung AS dijadwalkan mulai mendistribusikan bantuan di wilayah Gaza pada akhir Mei.
CNN melaporkan, GHF dipimpin oleh Jake Wood, seorang veteran militer AS yang juga merupakan pendiri dan pemimpin Team Rubicon, organisasi yang berfokus pada bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam.
Dalam memorandum yang menjelaskan tujuan mereka, GHF menyatakan, “Penyimpangan bantuan, pertempuran yang sedang berlangsung, dan akses yang terbatas telah menghalangi bantuan yang menyelamatkan nyawa sampai kepada orang-orang yang membutuhkan dan hal ini juga mengurangi kepercayaan para donor.”
“GHF didirikan untuk mengembalikan jalur bantuan yang sangat penting ini melalui model yang independen dan diaudit secara ketat, sehingga bantuan dapat disalurkan langsung—dan hanya—kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.”Dalam proses distribusi bantuan, GHF menyatakan akan berkoordinasi dengan militer Israel. Namun, pengamanan lokasi akan dilakukan oleh kontraktor militer swasta, termasuk sebuah perusahaan AS yang pernah beroperasi di lapangan selama gencatan senjata pada awal tahun ini.
Lantas, dari mana GHF mendapatkan makanan dan pendanaan? Belum jelas.
Dalam pengumumannya minggu ini, GHF mengatakan mereka berada dalam tahap akhir pengadaan bantuan makanan dalam jumlah besar untuk melengkapi janji-janji yang sudah ada dari organisasi-organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Gaza. Mereka menyebutkan jumlah bantuan tersebut setara dengan lebih dari 300 juta porsi makanan.
Namun, mereka tidak mencantumkan siapa pemasoknya.
Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee mengatakan pekan lalu bahwa sudah ada beberapa pihak yang berkomitmen untuk membantu pendanaan, namun mereka belum ingin diungkapkan untuk saat ini.
Demi Keamanan Israel Atau Keuntungan Netanyahu?

Memprioritaskan pembebasan para sandera di Gaza atau melanjutkan perang, inilah dua pertanyaan yang disebut memecah belah Israel hari-hari terakhir.
Pemerintah Israel, yang begitu terobsesi dengan mimpi menghancurkan Hamas secara total, telah menunjukkan tekad untuk terus berperang. Di balik sikap keras ini berdiri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kelompok nasionalis religius garis keras yang menopang kekuasaannya.
Mereka menginginkan agar warga Palestina di Gaza digantikan oleh pemukim Yahudi. Mereka mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu jika dia tidak melanjutkan perang.
Bagi Netanyahu sendiri, akhir dari karier politiknya akan membuka jalan bagi pertanggungjawaban atas kegagalannya mencegah serangan mematikan pada 7 Oktober 2023. Hal ini dapat pula mempercepat proses penyelesaian persidangan panjang atas tuduhan korupsi yang dihadapinya.
Netanyahu belum lama ini menjanjikan serangan baru yang intens ke Gaza, yang bahkan memicu protes dari para tentara cadangan Israel. Mereka menyatakan dipaksa bertempur kembali bukan demi keamanan Israel, melainkan demi kelangsungan politik pemerintahan Israel.
Sebanyak 1.200 pilot cadangan angkatan udara telah menandatangani surat terbuka yang menyatakan bahwa perpanjangan perang ini terutama melayani kepentingan politik dan pribadi, bukan kepentingan keamanan. Netanyahu menyalahkan sekelompok kecil pembangkang atas surat terbuka itu.
Israel selama ini berargumen bahwa tindakannya sejak 7 Oktober 2023 dapat dibenarkan sebagai bentuk pembelaan diri. Pemerintah manapun, menurut Israel, akan melakukan hal yang sama.
Namun, pihak Palestina, bersama dengan semakin banyak negara yang prihatin dan geram—termasuk beberapa sekutu utama Israel di Eropa—menyatakan bahwa argumen Israel tidak bisa membenarkan kelanjutan perang paling menghancurkan terhadap rakyat Palestina sejak 1948, ketika Israel merdeka. Peristiwa itu dikenang oleh warga Palestina sebagai “nakba” atau “malapetaka”.
Netanyahu pada Kamis mengonfirmasi bahwa dari 58 sandera yang masih berada di Gaza, 20 di antaranya diyakini masih hidup.