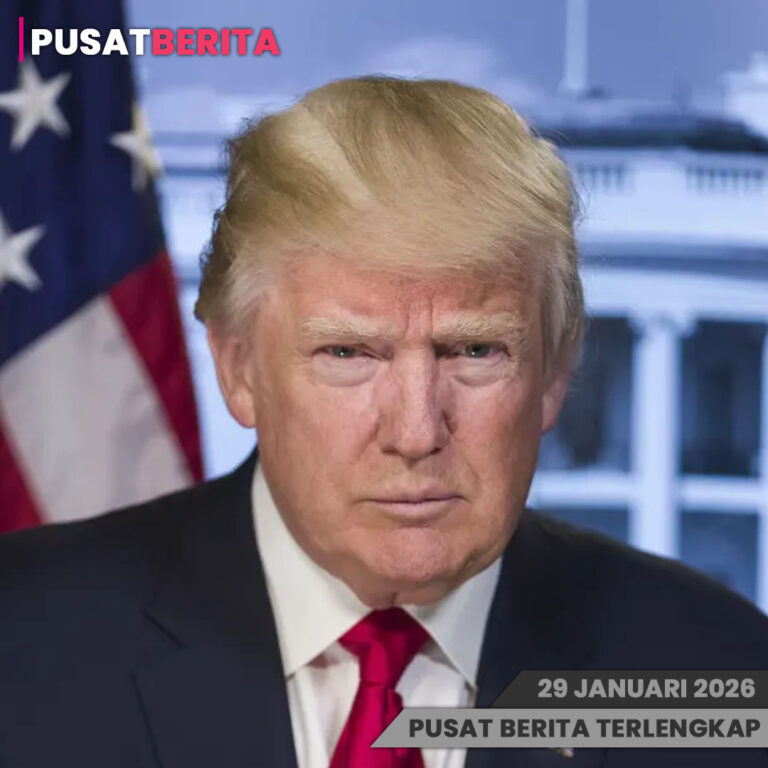Jakarta – Malam itu, suasana Warakas, Jakarta Utara, terasa sunyi. Momen ini biasa Rizal gunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya di ruang tengah. Namun, tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara gaduh yang datang dari luar rumah. Teriakan bersahutan, bunyi benturan benda keras, dan langkah kaki yang bergegas membuat jantungnya berdetak lebih cepat.
Ia mengintip dari balik jendela, dan di bawah cahaya remang lampu jalan, dua kelompok remaja tampak saling serang. Tawuran, seperti yang sudah sering ia dengar dan saksikan sejak bertahun-tahun lalu, kembali terjadi.
“Itu kejadian hampir jam dua atau tiga pagi. Rumah saya kan bukan di komplek, jadi masih rawan banget. Kampung sebelahan ribut, bisa langsung ke sini,” ujar Rizal.
Pria paruh baya yang sudah puluhan tahun tinggal di Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini mengungkapkan, pemandangan semacam itu bukan hal baru. Dalam setahun, ia mengaku bisa melihat dua hingga tiga insiden serupa.
Tapi malam itu terasa berbeda. Bukan hanya karena jaraknya begitu dekat dari rumah, melainkan juga karena kekerasan itu kini begitu nyata—bukan sekadar potongan video viral di media sosial.
“Ngeri kalau batu nyasar masuk pagar, bisa pecahin kaca mobil atau rumah. Bukan cuma saya yang takut, tetangga juga pada ngeri. Kalau ada kekerasan itu ngerembet ke mana-mana,” keluhnya.
Refleks, Rizal segera mengambil ponsel dan menghubungi grup WhatsApp RT serta menelepon Polsek Tanjung Priok. Ia tahu, tidak bisa tinggal diam ketika ancaman itu begitu dekat. Aksi cepat itu membuahkan hasil—kericuhan bubar dalam 20 menit, sebelum ada korban atau kerusakan berarti. Namun di balik perasaan lega itu, tersisa kegelisahan yang belum juga hilang. Ia khawatir hal ini terulang kembali.
Untuk itu, Rizal mendorong para remaja yang suka terlibat tawuran untuk dapat diberdayakan melalui kegiatan positif. “Mungkin bisa lewat karang taruna, komunitas atau pun patroli yang lebih rutin agar tidak ada ruang untuk mereka bertemu untuk tawuran,” harap dia.
Sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida Noor mengungkapkan, fenomena tawuran remaja tidak dapat lagi dipandang sebagai kenakalan biasa. Itu merupakan cermin dari masalah sosial struktural yang membutuhkan intervensi menyeluruh hingga ke akar persoalan.
“Tawuran bukan hanya gejala sosial, tapi merupakan masalah sosial, yang perlu ada intervensi hingga ke akar masalah,” kata dia, Rabu (14/5/2025).
Berdasarkan pengalamannya melakukan pendampingan pada kelompok remaja pelaku tawuran bersama tim dari Departemen Sosiologi UI, Ida menemukan salah satu akar masalah terletak pada kurangnya rekognisi terhadap kelompok remaja tertentu, terutama yang berasal dari kelas menengah bawah dan tinggal di kawasan padat penduduk.
“Yang tinggal di area padat penduduk, dan atau di sekolah-sekolah yang dianggap bukan favorit. Artinya mereka mengalami marginalisasi, bahkan juga stigmatisasi. Pemerintah Kota cenderung bias kelas menengah atas,” ujar dia
Situasi ini, kata Ida, menjadi latar terbentuknya kohesi sosial yang justru dibangun atas dasar kesadaran kolektif terhadap pembangunan kota yang tidak berkeadilan sosial.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan tindakan kekerasan remaja umumnya lebih dipicu oleh lingkungan sosial, khususnya peer group atau kelompok sebaya yang terbentuk di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal.
Dalam konteks ini, peran keluarga dan sekolah kerap kali tidak cukup kuat untuk menjadi kontrol sosial yang efektif.
“Upaya pencegahan seharusnya bisa berbasis komunitas, sinkronisasi peran keluarga, sekolah, dan infrastruktur sosial, khususnya kelompok-kelompok keagamaan di komunitas,” ujar dia.
Ia juga turut menyoroti peran media dalam membentuk pola pikir dan perilaku remaja. Tayangan kekerasan, dinilai ikut berkontribusi dalam membentuk pola perilaku antisosial yang ditiru oleh anak-anak muda.
“Catatan utama perlu ditujukan kepada media, termasuk film-film genre kekerasan, intensitas info-info atau tayangan kekerasan, termasuk kekerasan dari ormas-ormas atau pihak-pihak lain yang dijadikan rujukan (role model) dalam bersikap dan berperilaku. Negara harus ikut aktif mengontrol media, yang lebih dominan menayangkan perilaku anti sosial,” tandas dia.
Peneliti Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) yang juga sebagai Budayawan Betawi, Yahya Andi Saputra menilai tawuran yang marak terjadi di berbagai wilayah bukanlah bentuk dari budaya yang melekat dalam masyarakat. Menurut dia, tawuran berawal masalah personal yang meluas karena provokasi lingkungan sekitar.
“Tawuran ya tawuran, enggak ada unsur geser-menggeser makna (budaya pamer di sosmed). Itu urusan ketersinggungan dan dendam satu orang kepada orang laen,” kata dia, Rabu (14/5/2025).
Menurut Yahya, pemicu tawuran kerap kali berawal dari hal-hal sepele, bahkan tak jelas asal-usulnya. Namun, persoalan tersebut malah berkembang menjadi konflik kelompok karena adanya solidaritas sosial yang salah arah.
“Ketersinggungan ini diawali hal sapele atau enggak tau asal-muasalnya. Tiba-tiba saling bersitegang,” ujar dia.
Dalam pandangan Yahya, label tawuran sebagai budaya merupakan bentuk kekeliruan berpikir yang justru mengaburkan akar persoalan.
“Urusan pribadi yang melibatkan orang deket. Orang deket memprovokasi menjadi urusan bersama, urusan ketersinggungan dan harga diri orang sekampung. Urusan pribadi dibawa jadi urusan kelompok/kampung dll. Karena menahun, maka dianggap budaya. Itu konyol, bukan budaya,” ujar dia.
Yahya menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat, ketua RT/RW, atau bahkan untuk mencegah tawuran sekaligus membantu menciptakan lingkungan yang aman dan damai.
“Banyak lingkungan yang sangat heterogen malah rukun damai sentosa. Ya tentu saja lingkungan dan dedengkotnya punya peran penting bagi hidup rukun, tak terganggu dengan latar belakang SARA. Dedengkot punya peran penting mengedukasi masyarakat untuk hidup rukun,” tandas dia.
Sementara itu, Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis, menilai tawuran ini bukan fenomena yang bisa sepenuhnya dihapus. Dalam pandangannya, tawuran adalah ekspresi sosial yang melekat pada dinamika usia muda, khususnya remaja yang memiliki energi besar namun tidak tersalurkan secara sehat.
“Dalam setiap wawancara tentang tawuran, saya akan bilang ini nggak akan pernah hilang dari muka bumi. Karena akar masalahnya adalah anak muda yang sedang mencari pengakuan dan eksistensi,” ujar Rissalwan saat dihubungi, Selasa (13/5/2025).
Menurutnya, remaja di usia belasan hingga awal 20-an adalah kelompok usia dengan dorongan tinggi untuk terlihat, diterima, dan diakui dalam lingkungannya. Maka, mereka cenderung membentuk kelompok, mencari identitas, dan tak jarang melampiaskan energinya melalui konflik. Tawuran, dalam hal ini, menjadi bentuk kompetisi yang salah arah.
Rissalwan menjelaskan bahwa sebenarnya kebutuhan remaja untuk bertanding dan menunjukkan diri bisa dialihkan ke kegiatan yang lebih positif seperti olahraga. Namun, tidak semua lingkungan di Jakarta memiliki fasilitas yang mendukung. Di kawasan padat penduduk, akses terhadap lapangan, pusat komunitas, atau ruang berekspresi cenderung minim, tak seperti kawasan elit atau kompleks perumahan yang lebih tertata.
“Anak-anak di lingkungan menengah ke bawah sering tak punya ruang yang cukup untuk berekspresi. Di sisi lain, mereka tetap butuh validasi. Kalau anak-anak kompleks bisa pamer di sosial media dengan liburan atau barang mahal, yang ini mungkin cuma bisa tampil lewat aksi ekstrem,” jelasnya.
Dalam konteks kekinian, media sosial justru memperparah situasi. Tawuran kini tidak semata untuk membuktikan kekuatan fisik, tapi juga demi konten yang bisa viral. Rissalwan menyoroti fenomena remaja membawa senjata tajam besar hanya untuk menakuti atau menciptakan efek dramatis di dunia maya.
“Bisa jadi, mereka nggak benar-benar berani tawuran. Senjata tajam itu cuma alat buat nakut-nakutin. Satu setengah meter panjangnya, apa bisa diayunkan dengan efektif? Ini lebih ke bluffing, bukan niat serius melukai,” katanya.
Rissalwan menekankan, solusi untuk persoalan ini tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan. Energi besar yang dimiliki anak muda perlu difasilitasi lewat ruang-ruang aman dan produktif, baik oleh keluarga, sekolah, maupun komunitas sekitar. Ia juga menyinggung pentingnya peluang kerja dan peran orang tua dalam membentuk pola pikir remaja.
“Anak muda itu sangat tergantung pada lingkungan luarnya: orang tua, guru, tokoh masyarakat. Kalau salah pola asuh atau tidak ada ruang interaksi positif, maka mereka bisa berontak. Jadi bukan anak mudanya yang salah, tapi sistem sosial di sekitarnya harus berbenah,” tegasnya.
Bagi Rissalwan, tawuran bukan sekadar soal pelanggaran hukum. Ia adalah sinyal bahwa ada bagian dari masyarakat yang sedang kehilangan arah dan ruang. Maka penanganannya pun harus lebih dari sekadar patroli—melainkan perubahan sistemik yang melibatkan semua elemen.
Majelis Bersholawat Jadi Solusi?

Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal menggelar kegiatan Manggarai Bersholawat. Menurut dia, hal tersebut menjadi langkah mencari akar masalah dari seringnya kegiatan tawuran di wilayah tersebut.
“Saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersholawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana. Ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu. Duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya? Karena gak bisa hanya menyalahkan saja,” kata Pramono saat ditemui di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2025).
Pramono menjelaskan, cara Manggarai bersholawat adalah salah satu contoh. Nantinya, di wilayah lain yang terjadi tawuran akan menggunakan pendekatan berbeda dengan menyesuaikan karakter masing-masing.
“Ya ini (Manggarai Bersholawat) kan baru contoh saja. Tentunya yang lain ada (cara berbeda),” tutur dia.
Secara teknis, Pramono menyebut Manggarai Bersholawat akan mengajak semua pihak duduk bersama. Hal itu dikarenakan mayoritas agama di wilayah tersebut beragama Islam.
Nantinya, dia juga akan melibatkan tidak hanya tokoh masyarakat, tetapi juga tokoh keagamaan.
“Jadi kita aja duduk bareng, karena mayoritas di Manggarai ini kan agamanya Islam. Sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama dan semuanya dilibatkan stakeholder yang ada, saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu,” Pramono memungkasi.
Pramono mengaku sudah mempelajari substansi dari seringnya tawuran di Jakarta. Menurut dia, salah satu masalahnya dikarenakan faktor ekonomi. Ia mengamati, mereka yang terlibat umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Secara substansi, karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana mohon maaf belum punya pekerjaan tetap,” ungkap Pramono.
“Kemudian ada sarana olahraga dan sarana-sarana lain yang tidak termanfaatkan secara baik,” imbuhnya.
Sebagai gubernur Jakarta, Pramono berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki permasalahan warga kotanya yang kerap tawuran.
“Pokoknya sebagai gubernur Jakarta, saya nggak mau ngomongin tempat lain. Tetapi saya bertanggung jawab terhadap warga Jakarta untuk memperbaiki itu,” janji dia.
Sementara itu, sambung Pramono, salah satu cara yang akan ditempuh adalah membuat pendekatan khusus melalui kultural dan sisi keagamaanya. Dia berharap dengan dua langkah itu, maka para pelaku tawuran bisa berperilaku lebih baik.
“Sehingga dengan demikian ada pedekatan kultural, keagamaan, orang dihargai,” Pramono menandasi.